Ada yang berdesir di hati tatkala membaca berita tentang sistem penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN). Besarnya uang sumbangan - atau apapun istilahnya - yang ditetapkan sebagai salah satu syarat bagi para calon mahasiswa PTN yang tidak melalui jalur ujian masuk PTN (UMPTN), sebenarnya sebangun dengan sistem seleksi mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta (PTS).
Uang sumbangan sejatinya bukan faktor tunggal penentu diterima atau tidaknya seorang lulusan SMA di PTS. Namun, sukar dipungkiri, fokus perhatian para calon mahasiswa, termasuk orang tua mereka, lebih tertuju pada masalah uang ini. Ada kepercayaan bahwa semakin besar uang yang disumbangkan, semakin besar pula peluang diterimanya calon mahasiswa yang bersangkutan.
Kesan signifikansi dana sumbangan semakin kentara, karena - seingat penulis - jumlah uang yang akan diberikan kepada PTS sudah dimasukkan sebagai salah satu butir pertanyaan pada lembar pendaftaran ujian masuk. Seleksi tertulis dan wawancara bagi calon mahasiswa, tak ayal, dipandang sebagai formalitas belaka.
Anggapan semacam itu, keliru maupun tidak, menunjukkan bahwa keberhasilan seorang calon mahasiswa PTS dalam proses seleksi ternyata sangat tergantung pada kesiapan para orang tua dalam 'memperjuangkan' anak mereka. Sepanjang mengikuti seluruh mekanisme yang ada, dan memberikan uang sumbangan yang ''memadai, gerbang PTS terbuka bagi si jebolan SMA. Dalam terminologi psikologi, dinamika ini disebut sebagai atribusi eksternal, yang bermakna bahwa unsur-unsur eksternal menjadi kausa utama bagi masuknya mahasiswa baru ke PTS.
Pada saat yang sama, secara umum, PTN tidak mensyaratkan uang sumbangan kepada para calon mahasiswa. Para peminat tidak perlu menimbang-nimbang besarnya anggaran yang akan dialokasikan guna membuka pintu PTN. Yang penting adalah, pertama, belajar sebaik mungkin selama di SMA, sehingga berpeluang terpilih masuk PTN melalui program penelusuran bakat, minat, dan prestasi akademik. Atau, alternatif kedua, mengikuti seleksi nasional melalui UMPTN.
Bagi orang tua, uang bisa jadi berperan penting untuk kemungkinan kedua di atas. Bukan untuk dana sumbangan, melainkan untuk memberikan kursus tambahan bagi si buah hati agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya saat mengerjakan soal-soal UMPTN. Tanpa kursus ekstra, persiapan bersaing di ajang UMPTN terasa kurang afdol.
Ditambah oleh beraneka jaminan yang diberikan oleh lembaga-lembaga bimbingan tes, pada gilirannya terbangun sebuah keyakinan bahwa keikutsertaan dalam program bimbingan UMPTN merupakan jembatan menuju PTN. Tentor-tentor di lembaga kursus, oleh tidak sedikit kalangan, dinilai lebih mumpuni ketimbang guru-guru di SMA dalam menguasai sekaligus mengajarkan keterampilan yang diperlukan siswa sewaktu mengerjakan soal-soal UMPTN.
Periode waktu menjelang UMPTN tidak hanya menegangkan bagi si calon mahasiswa, tetapi juga bagi orang tua, bahkan keluarga besarnya. Kendati demikian, ketika UMPTN berlangsung, tidak ada yang dapat diperbuat oleh orang tua, kecuali memberikan semangat dan berdoa. Kegagalan, secara manusiawi, akan mengecewakan. Sebaliknya, tercantumnya nama si anak di dalam daftar pengumuman mahasiswa baru PTN di surat-surat kabar daerah - biasanya sudah laris terbeli sejak dini hari - akan diikuti dengan sujud syukur dan kenduri.
Begitu dramatisnya kronologi penerimaan mahasiswa baru PTN, sehingga PTN menjadi luar biasa prestisius. Tidak hanya disebabkan seleksinya yang ketat, tetapi termasuk pula karena terjangkaunya biaya yang harus dikeluarkan. Belum lagi segala atribut tridharma perguruan tinggi yang tampak lebih murni di PTN ketimbang non-PTN.
Jelas, adalah si anak sendiri yang pada akhirnya harus berjibaku agar dapat lolos dari lubang jarum. Wajar apabila ia bersuka dan berbangga hati, karena kesuksesan menjadi mahasiswa PTN adalah produk atribusi internal. Hasil perasan otak, kucuran peluh, dentuman jantung, dan bisikan doa si anak 'sendiri'.
Hingga saat ini, lika-liku masuk PTN masih ada. Hanya saja, mulai sekarang, dua mekanisme penerimaan mahasiswa PTN - UMPTN dan rekrutmen atas dasar prestasi belajar di SMA - didampingi oleh sistem baru yang memberikan garis bawah pada pentingnya uang sumbangan dari para lulusan SMA yang ingin masuk PTN.
Pemberlakuan sistem mutakhir ini tentu didahului oleh banyak pemikiran. Yang susah untuk dipikir, setidaknya oleh penulis, adalah bahwa perkembangan ini telah memberikan gambaran bahwa dunia pendidikan tinggi di Tanah Air seolah berlawanan arus dengan kondisi faktual negeri ini.
Ketika kemorat-maritan belum pupus dari berbagai dimensi kehidupan, lingkungan perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi satu-satunya lingkungan yang peka terhadap kondisi nyata tersebut. Dalam prakteknya, menyikapi anjloknya kemampuan masyarakat dalam bersekolah sebagai akibat krisis ekonomi, perguruan tinggi yang steril dari dekadensi moral seyogianya justru membuka pintu lebih lebar bagi setiap warga bangsa untuk memperoleh kesempatan menuntut ilmu.
Dalam konteks ini, penerimaan mahasiswa baru melalui sistem baru memang merupakan manifestasi terbukanya peluang lebih luas bagi siapapun untuk berkuliah. Semua pihak, tak terkecuali yang berasal dari keluarga yang sangat berkemampuan, mempunyai hak untuk mengirimkan anak mereka ke PTN.
Permasalahannya, direnungi lebih lanjut, penetapan syarat berupa dana sumbangan yang sedemikian tinggi adalah tidak paralel dengan keadaan masyarakat luas dewasa ini pada umumnya. Sistem baru ini memberikan keuntungan finansial besar bagi PTN, tapi seberapa jauh sistem ini dapat memperbesar peluang para lulusan SMA agar dapat mengenyam pendidikan di PTN? Lebih lugas lagi, pihak mana sajakah yang kesempatannya untuk masuk PTN semakin besar, akibat pemberlakuan mekanisme baru ini?
Penerimaan mahasiswa melalui UMPTN maupun penelusuran prestasi akademik di SMA, keduanya menandaskan kompetisi akademik. Sedangkan pada sistem rekrutmen yang mulai dipraktekkan oleh banyak PTN, persaingan memasuki lingkungan akademik naifnya didominasi oleh faktor non-akademik. Sehingga, alih-alih memancarkan jiwa empati terhadap keprihatinan yang dialami kelompok masyarakat yang berasal dari golongan ekonomi lemah, format baru dalam penerimaan mahasiswa baru justru lebih memfasilitasi anggota masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi lebih dari sekedar mampu dalam rangka memasuki PTN.
Realita ini hanya menambah deretan distorsi yang telah ada di dunia pendidikan nasional pada waktu-waktu belakangan ini. Seperti banyak diberitakan media massa, kasus ijazah palsu semakin marak. Pelakunya, tak tanggung-tanggung, para pejabat lokal dan nasional. Sudah barang tentu, para pemilik ijazah palsu ini bukan merupakan sosok-sosok berekonomi lemah, mengingat mahalnya harga ijazah palsu yang harus mereka bayar.
Setali tiga uang, munculnya gelar-gelar akademik aspal. Hanya dengan menghadiri beberapa kali tatap muka dan - kadang - menulis 'tesis' maupun 'disertasi', seorang mahasiswa dapat lulus dengan menyandang gelar akademik sesuai selera. Lagi-lagi, hanya mereka yang bersaku tebal yang sanggup membeli gelar prestise semacam itu.
Keinginan publik untuk menggenggam ijazah dan gelar akademik - tanpa harus mengikuti kegiatan perkuliahan sebagaimana mestinya - disambut oleh banyak lembaga-lembaga edukasi partikelir. Mereka, yang sejatinya hanya menyelenggarakan pendidikan setara kursus, mengelabui masyarakat dengan menawarkan gelar D3 (setingkat sarjana muda) serta menganugerahkan ijazah berikut seremoni dan toga di gedung-gedung mewah.
Program 'perkuliahan' jangka pendek serta gelar akademik adalah iming-iming yang gencar dipromosikan oleh institusi-institusi pendidikan - termasuk perguruan tinggi - imajiner tersebut. Jangankan penumbuhkembangan budi pekerti, transfer ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi pun jauh panggang dari api. Tetapi celakanya, kepraktisan seperti inilah yang, kendati mahal, nyatanya kini kian digandrungi. Siapa lagi yang dapat membeli hal-hal superfisial dan artifisial tersebut, jika bukan mereka yang bersumber daya keuangan besar.
Sekali lagi, penulis percaya, ada banyak pertimbangan di balik penyelenggaraan sistem seleksi yang berbasis pada besaran uang sumbangan ini. Sebagian besar, untuk tidak mengatakan semuanya, dapat diterima nalar. Namun, hemat penulis, perguruan tinggi bukanlah sebuah instansi yang dibangun semata di atas pondasi nalar. Ia dibangun dengan penuh idealisme sebagai sebuah kawah candradimuka bagi calon-calon intelektual. Bagi individu masa depan yang kepeduliannya telah melampaui batas-batas diri sendiri serta menjangkau kehidupan individu-individu lain. Tak lain, manusia yang berhati nurani - tak hanya bernalar - yang mampu menjelma menjadi sosok sedemikian rupa.
Implikasinya, setiap perguruan tinggi sepantasnya juga berdiri dengan nurani sebagai salah satu tiang pancangnya. Penekanan sekaligus pembinaan terhadap nurani seyogianya sudah mulai dilakukan sejak seorang lulusan SMA berencana akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Dan, proses selektif yang menempatkan daya juang individu - bukan pihak lain - sebagai kunci keberhasilan, merupakan sebuah sistem yang berfungsi sebagai pelontar bagi siapapun yang ingin bertransformasi dari siswa menjadi mahasiswa. Siswa yang mengemban tanggung jawab besar di balik kata maha yang mereka sandang!
Tidak mutlak bahwa semua mahasiswa PTN yang diterima melalui jalur UMPTN dan prestasi akademik di SMA niscaya akan berkualitas lebih tinggi daripada mahasiswa PTN yang memasuki kampus melalui sistem yang baru ini. Pun, inisiatif PTN mengadakan mekanisme penerimaan mahasiswa baru melalui penekanan pada uang sumbangan dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari adanya kebutuhan akan sumber dana penyelenggaraan pendidikan yang lebih besar.
Terlepas dari kemafhuman akan hal-hal di atas, sistem baru penerimaan mahasiswa PTN dapat ditafsirkan sebagai bentuk perlakuan istimewa yang diterapkan PTN bagi para calon mahasiswa dari keluarga berekonomi mapan. Apabila langkah tersebut dinilai sah-sah saja, maka agar adil kemudahan macam apa yang akan diberikan - apalagi diperluas - kepada mereka yang tidak mampu bersaing di dalam sistem baru ini? Wallaahu a'lam.
Profil
nama saya wahyu dwiato septiansyah,saya lahir pada tanggal 29 September 1989. biasanya teman - teman memanggil saya tito,karena itu memang nama pangilan saya. saya merupakan anak ke-4 dari empat bersaudara. bisa dibilang saya adalah anak bontot. kata orang, anak bontot merupakan anak yang selalu dimanja oleh ke-2 orang tuanya. namun, saya tidak menampik itu semua,karena saya sangat merasakan perhatian lebih yang diberikan oleh ke-2 orang tua saya. di saat saya memasuki usia 5 thn, saya didaftarkan di sebuah taman kanak - kanak yang ada di lingkungan sekitar rumah saya yang bernama taman kanak - kanak putra III. setelah itu, saya mulai mengenyam pendidikan TK disana kira - kira selama 1 thn lamanya. menurut teman saya, saya merupakan anak yang bisa dibilang nakal. pada suatu hari, saya bertengkar dengan teman saya di TK tersebut karena dia tidak diajak main dengan teman - teman yang lainnya. lalu dia pun, mendorong saya hingga saya terjatuh. setelah itu, saya pun membalasnya hingga dia menangis. saya juga pernah membuang air besar di celana,lalu saya dikurung oleh ibu guru di dalam dapur. mungkin semua hal itu tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup saya. setelah lulus TK, saya memasuki jenjang sekolah dasar. sekolah dasar yang saya masuki bernama SD 05 pagi yang tepatnya berada di daerah Bendungan Hilir. disana saya mendapaatkan kesenjangan sosial yang saya rasa amat pahit. saya pernah berfikir, mungkin saya salah masuk sekolah. karena disana merupakan sekolah yang bisa dibilang elit. mengapa saya bisa bilang elit, sebagian besar murid - murid yang bersekolah disana merupakan anak - anak yang jedua orang tuanya bisa dibilang mapan. walau begitu, saya tidak pernah minder untuk berkawan dengan mereka seada sebumua. saya pun akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan sekolah dasar selama 6 thn. setelah lulus SD, saya melanjutkan sekolah saya ke sekolah lanjutan tingkat pertama. sekolah itu bernama SLTP Negeri 40 jakarta yang tepatnya berada di Bendungan Hilir.setelah itu, saya melanjutkan sekolah saya ke sebuah SMA negeri yang ada di Jakarta, sekolah itu bernama SMA Negeri 7 Jakarta yang tepatnya berada di daerah Karet Tengsin. setelah lulus SMA, saya merasa bingung untuk menempuh jalan mana yang harus saya ambil. di satu sisi saya ingin kuliah tapi di sisi lain saya juga ingin bekerja. akhirnya saya mengikuti perintah orang tua saya untuk kuliah. setelah itu, saya memutuskan untuk menempuh jalur SPMB dan alhamdulillah saya lulus. sebenarnya ada dua pilihan dalam SPMB yang pertama saya memilih manajemen dan pendidikan tata niaga. ternyata saya diterima di prodi pendidikan tata niaga. walau begitu, saya merasa bersyukur bisa kuliah di salah satu Universitas Negeri di Jakarta. saya pun bisa membuktikan kepada orang tua saya, bahwa saya benar - benar telah berubah. jika ditanya prestasi, sejak kecil saya tidak pernah mendapatkan ranking. namun, saya pernah memenangkan kejuaraan sepak bola dan saya mendapatkan juara 3.mungkin hanya itu prestasi yang saya raih. harapan saya adalah ingin membahagiakan kedua orang tua saya terlebih dahulu dan saya ingin membuktikan bahwa saya bisa melakukan itu semua. cita - cita saya adalah ingin menjadi warga yang berguna bagi nusa dan bangsa dan saya ingin menjadi anggota legislatif di DPR.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
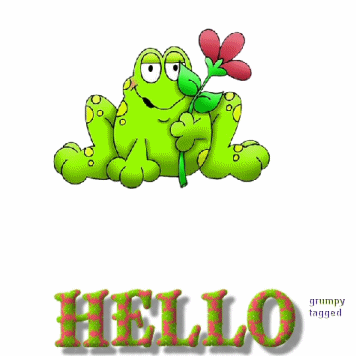
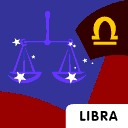

Tidak ada komentar:
Posting Komentar